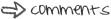Nama : Achda Fitriah
Nama : Achda Fitriah
NIM : 11140163000007
Kelas : Fisika 2A
Nama Blog : PHYSICS ZONE
Apa Sih Konsep Diri Itu?
Baron dan Byrne mengatakan konsep diri merupakan sekumpulan fungsi yang kompleks yang berbeda yang dipegang oleh seseorang tentang dirinya[1]. MenurutWilliam D. Broks mendefinisikan konsep diri adalah pandangan dan perasaan tentang kita, yang bersifat psikologi, sosial, dan fisis[2]. Menurut Sulaeman, konsep diri adalah kesluruhan ide-ide dan sikap-sikap seseorang sebagai apa dan siapa dia[3]. Suryabrata menyatakan konsep diri mempunyai empat aspek, yaitu bagaimana orang mengamati dirinya sendiri, bagaimana orang berpikir tentang dirinya sendiri, bagaimana orang menilai dirinya sendiri, bagaimana berusaha dengan berbagai cara untuk menyampaikan dan mempertahankan diri[4]. Calhoun dan Acocela (1990) menyatakan konsep diri adalah gambaran mental individu yang terdiri dari pengetahuannya tentang diri sendiri, pengharapan bagi diri sendiri, dan penilaian terhadap diri sendiri[5]. Konsep diri di dalam Islam, Allah SWT berfirman dalam Q.S. At-Taghabun ayat 16 yang artinya :
“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.”
Dari uraian di atas dapat disimpulkan pengertian konsep diri adalah cara individu memandang dirinya secara utuh, baik fisikal, emosional, intelektual, sosial, dan spiritualterhadap masyarakat, lingkungan maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsep Diri
Kerangka Menurut Stuart dan Sudeen ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan konsep diri. Faktor-faktor tersebut terdiri dari teori perkembanganSignificant Other (orang yang terpenting atau yang terdekat ) dan Self Perception(persepsi diri sendiri)[6].
a. Teori Perkembangan
Konsep diri berkembang secara bertahap sejak lahir seperti mulai mengenal dan membedakan dirinya dan orang lain. Dalam melakukan kegiatannya memiliki batasan diri yang terpisah dari lingkungan dan berkembang melalui kegiatan eksplorasi lingkungan melalui bahasa, pengalaman atau pengenalan tubuh, nama panggilan, pengalaman budaya dan hubungan interpersonal, kemampuan pada area tertentu yang dinilai oleh diri sendiri atau masyarakat serta aktualisasi diri dengan merealisasi potensi yang nyata.
b. Significant Other (Orang Terpenting atau Terdekat)
Konsep diri dipelajari melalui kontak dan pengalaman dengan orang lain, belajar diri sendiri melalui cermin orang lain yaitu dengan cara pandangan diri merupakan interpretasi diri pandangan orang lain terhadap diri, anak sangat dipengaruhi orang yang dekat, remaja dipengaruhi oleh orang lain yang dekat dengan dirinya, pengaruh orang dekat atau orang penting sepanjang siklus hidup, pengaruh budaya dan sosialisasi.
c. Self Perception (Persepsi Diri Sendiri)
Yaitu persepsi individu terhadap diri sendiri dan penilaiannya, serta persepsi individu terhadap pengalamannya akan situasi tertentu. Konsep diri dapat dibentuk melalui pandangan diri dan pengalaman yang positif. Sehingga konsep merupakan aspek yang kritikal dan dasar dari prilaku individu. Individu dengan konsep diri yang positif dapat berfungsi lebih efektif yang dapat berfungsi lebih efektif yang dapat dilihat dari kemampuan interpersonal, kemampuan intelektual dan penguasaan lingkungan. Sedangkan konsep diri yang negatif dapat dilihat dari hubungan individu dan sosial yang terganggu. Menurut Stuart dan Sundeen penilaian tentang konsep diri dapat dilihat berdasarkan rentang-rentang respon konsep diri, yaitu
d. Aktualisasi Diri
Aktualisasi diri adalah pernyataan diri tentang konsep diri yang positif dengan latar belakang pengalaman yang nyata yang sukses dan diterima.
e. Konsep Diri Positif
Konsep diri positif apabila individu memiliki pengalaman yang positif dalam beraktualisasi diri.
f. Harga Diri Rendah
Harga diri rendah adalah transisi antara respon konsep diri adaptif dengan respon konsep diri maladaptif.
g. Kerancuan Identitas
Kekacauan identitas adalah kegagalan individu mengintegrasikan aspek – aspek identitas masa kanak – kanak ke dalam kematangan aspek psikososial kepribadian pada masa dewasa yang harmonis.
h. Depersonalisasi
Depersonalisasi adalah perasaan yang tidak realistis dan asing terhadap diri sendiri yang berhubungan dengan kecemasan, kepanikan serta tidak dapat membedakan dirinya dengan orang lain.
B. Pembagian Konsep Diri
Untuk Konsep diri terbagi menjadi beberapa bagian. Pembagian konsep diri tersebutdikemukakan oleh Stuart dan Sundeen (1991), yang terdiri dari[7] :
1. Pola Gambaran Diri (Body Image)
Gambaran diri adalah sikap seseorang terhadap tubuhnya secara sadar dan tidak sadar. Sikap ini mencakup persepsi dan perasaan tentang ukuran, bentuk, dan fungsi penampilan dan potensi tubuh saat ini dan masa lalu yang secara berkesinambungan dimodifikasi dengan pengalaman baru setiap individu (Stuart and Sundeen, 1991)[8]. Sejak lahir individu mengeksplorasi bagian tubuhnya, menerima stimulus dari orang lain, kemudian mulai memanipulasi lingkungan dan mulai sadar dirinya terpisah dari lingkungan (Keliat, 1992)[9]. Gambaran diri berhubungan dengan kepribadian. Cara individu memandang dirinya mempunyai dampak yang penting pada aspek psikologisnya. Individu yang stabil, konsisten dan realistis terhadap gambaran dirinya akan memperlihatkan kemampuan yang mantap terhadap realisasi yang akan memacu sukses dalam kehidupan. Menurut Potter dan Perry (2005), Body imageberkembang secara bertahap selama beberapa tahun dimulai sejak anak belajar mengenal tubuh dan struktur, fungsi, kemampuan dan keterbatasan mereka. Body image (citra tubuh) dapat berubah dalam beberapa jam, hari, minggu atau pun bulan tergantung pada stimuli eksterna dalam tubuh dan perubahan aktual dalam penampilan, stuktur dan fungsi[10].
2. Ideal Diri
Ideal diri adalah persepsi individu tentang bagaimana ia seharusnya bertingkah laku berdasarkan standar pribadi. Standar dapat berhubungan dengan tipe orang yang diinginkan/disukainya atau sejumlah aspirasi, tujuan, nilai yang diraih. Ideal diri akan mewujudkancita-cita ataupun penghargaan diri berdasarkan norma-norma sosial di masyarakat tempat individu tersebut melahirkan penyesuaian diri. Ideal diri berperan sebagai pengatur internal dan membantu individu mempertahankan kemampuan menghadapi konflik atau kondisi yang membuat bingung. Ideal diri penting untuk mempertahankan kesehatan dan keseimbanganmental. Pembentukan ideal diri dimulai pada masa anak-anak dipengaruhi oleh orang yang dekat dengan dirinya yang memberikan harapan atau tuntunan tertentu. Seiring dengan berjalannya waktu individu menginternalisasikan harapan tersebut dan akan membentuk dari dasar ideal diri. Pada usia remaja, ideal diri akan terbentuk melalui proses identifikasi pada orang tua, guru dan teman. Pada usia yang lebih tua dilakukan penyesuaian yang merefleksikan berkurangnya kekuatan fisik dan perubahan peran serta tanggung jawab[11]. Menurut Anna Keliat (2005), ada beberapa faktor yang mempengaruhi ideal diri, yaitu[12] :
a. Kecenderungan individu menetapkan ideal pada batas kemampuannya.
b. Faktor budaya akan mempengaruhi individu menetapkan ideal diri.
c. Ambisi dan keinginan untuk melebihi dan berhasil, kebutuhan yang realistis, keinginan untuk mengklaim diri dari kegagalan, perasaan cemas dan rendah diri.
d. Kebutuhan yang realistis.
e. Keinginan untuk menghidari kegagalan.
f. Perasaan cemas dan rendah diri.
Ideal diri hendaknya ditetapkan tidak terlalu tinggi, tetapi masih lebih tinggi darikemampuan agar tetap menjadi pendorong dan masih dapat dicapai.
3. Harga Diri
Harga diri adalah penilaian pribadi terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisis seberapa banyak kesesuaian tingkah laku dengan ideal dirinya. Harga diri diperoleh dari diri sendiri dan orang lain, yaitu dicintai, dihormati dan dihargai. Mereka yang menilai dirinya positif cenderung bahagia, sehat, berhasil dan dapat menyesuaikan diri, sebaliknya individu akan merasa dirinya negatif, relatif tidak sehat, cemas, tertekan, pesimis, merasa tidak dicintai atau tidak diterima di lingkungannya[13]. Harga diri dibentuk sejak kecil dari adanya penerimaan dan perhatian. Harga diri akan meningkat sesuai dengan meningkatnya usia. Harga diri akan sangat mengancam pada saat pubertas, karena pada saat ini harga diri mengalami perubahan, karena banyak keputusan yang harus dibuat menyangkut dirinya sendiri. Harga diri tinggi terkait dengan ansietas yang rendah, efektif dalam kelompok dan diterima oleh orang lain. Harga diri rendah terkait dengan hubungan interpersonal yang buruk, resiko terjadi depresi, dan skizofrenia. Gangguan harga diri dapat digambarkan sebagai perasaan negatif terhadap diri sendiri termasuk hilangnya percaya diri dan harga diri.
4. Identitas
Identitas adalah pengorganisasian prinsip dari kepribadian yang bertanggung jawab terhadap kesatuan, kesinambungan, konsistensi, dan keunikan individu.Mempunyai konotasi otonomi dan meliputi persepsi seksualitas seseorang.Pembentukan identitas dimulai pada masa bayi dan seterusnya berlangsung sepanjang kehidupan tapi merupakan tugas utama pada masa remaja[14]. Pada masa anak- anak , untuk membentuk identitas dirinya, anak harus mampu membawa semua perilaku yang di pelajari kedalam keutuhan yang koheren , konsisten dan unik. Rasa identitas ini secara kontiniu timbul dan di pengaruhi oleh situasi sepanjang hidup. Pada masa remaja , banyak terjadi perubahan fisik, emosional, kognitif dan social. Dimana dalam masa ini apabila tidak dapt memenuhi harapan dorongan diri pribadi dan social yang membantu mendefinisikan tentang diri maka remaja ini dapat mengalami kebingungan identitas. Seseorang dengan rasa identitas yang kuat akan merasa terintegrasi bukan terbelah.
5. Peran (Role Performance)
Peran adalah serangkaian pola perilaku yang diharapkan oleh lingkungan sosial berhubungan dengan fungsi individu di berbagai kelompok sosial. Peran yang ditetapkan adalah peran dimana seseorang tidak mempunyai pilihan. Peran yang diterima adalah peran yang terpilih atau dipilih oleh individu[15]. Peran adalah sikap dan perilaku nilai serta tujuan yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisinya di masyarakat. Harga diri yang tinggi merupakan hasil dari peran yang memenuhi kebutuhan dan cocok dengan ideal diri. Posisi di masyarakat dapat merupakan stressor terhadap peran karena struktur sosial yang menimbulkan kesukaran, tuntutan serta posisi yang tidak mungkin dilaksanakan[16].
C. Konsep Diri Positif dan Konsep Diri Negatif
Menurut Calhoun dan Acocela (1990),[17] dalam perkembangannya konsep diri terbagi menjadi dua, yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif.
1. Konsep Diri Positif
Konsep diri positif kepada penerimaan diri bukan sebagai suatu kebanggaan yang besar tentang diri.Konsep diri yang positif bersifat stabil dan bervariasi.Individu yang memiliki konsep diri positif adalah individu yang tahu betul tentang dirinya.
Individu dapat memahami dan menerima sejumlah fakta yang sangat bermacam-macam tentang dirinya sendiri, evaluasi terhadap dirinya sendiri menjadi positif dan dapat menerima keberadaan orang lain.
Individu yang memiliki konsep diri positif akan merancang tujuan-tujuan yang sesuai dengan realitas, yaitu tujuan yang memiliki kemungkinan besar untuk dapat dicapai, mampu menghadapi kehidupan di depannya serta menganggap bahwa hidup adalah suatu proses penemuan. Singkatnya, individu yang memiliki konsep diri positif adalah individu yang tahu betulsiapa dirinya sehingga dirinya menerima segala kelebihan dan kekurangan, evaluasi terhadap dirinya menjadi lebih positif dan mampu merancang tujuan-tujuan yang sesuai dengan realitas.
Seseorang yang memiliki konsep diri positif memiliki karakterikstik seperti berikut:
a. Merasa sanggup menyelesaikan masalah yang terjadi. Pemahaman diri terhadap kemampuan subyektif dalam menyelesaikan masalah-masalah obyektif yang dihadapi.
b. Merasa sepadan dengan orang lain. Seseorang yang memiliki konsep diri positif memiliki pemikiran bahwa saat dilahirkan manusia tidak membawa kekayaan dan pengetahuan. Kekayakan dan pengetahuan bisa dimiliki dari bekerja dan proses belajar selama hidup. Hal inilah yang mendasari sikap seseorang yang tidak merasa kurang ataupun lebih dari orang lain.
c. Tidak malu saat dipuji. Konsep diri positif membangun pribadi yang memiliki pemahaman bahwa pujian atau penghargaan layak diterima seseorang berdasarkan hasil yang telah dicapainya.
d. Merasa mampu memperbaiki diri. Dengan memiliki konsep diri positif seseorang akan merasa mampu untuk memperbaiki sikap yang dirasa kurang.
Dalam al-qur’an Allah berfirman mengenai konsep diri positif yaitu dalam sura ali imron ayat 139 dan fusshilat ayat 30.
وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
”Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman”. (Ali Imran: 139)
إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ
Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Tuhan kami ialah Allah” kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan): “Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih; dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu”. (Fusshilat: 30).
2. Konsep Diri Negatif
Calhoun dan Acocela membagi konsep diri negatif menjadi dua tipe, yaitu : Pandangan individu tentang dirinya sendiri benar-benar tidak teratur, tidak memiliki perasaan kestabilan dan keutuhan diri. Individu tersebut benar-benar tidak tahu siapa dirinya, kelebihan dan kelemahannya atau cara hidup yang tepat. Singkatnya, individu yang memiliki konsep diri negatif terdiri dari 2 tipe, tipe pertama yaitu individu yang tidak tahu siapa dirinya dan tidak mengetahui kekurangan dan kelebihannya, sedangkan tipe kedua adalah individu yang memandang dirinya dengan sangat teratur dan stabil. Seseorang dengan konsep diri negatif akan menunjukkan karakteristik seperti berikut ini:
a. Sensitif terhadap kritik. Pemilik konsep diri negatif biasanya kurang bisa menerima kritik dari orang lain sebagai upaya refleksi diri.
b. Senang dengan pujian. Sikap berlebihan terhadap tindakan yang dilakukan sehingga merasa perlu mendapat penghargaan terhadap segala tindakannya.
c. Merasa tidak disukai orang lain. Selalu muncul anggapan bahwa orang lain disekitarnya akan memandang negatif terhadap dirinya.
d. Suka mengkritik orang lain. Meski tidak suka dikritik namun pribadi ini senang sekali menghujani kritikan negatif kepada orang lain.
e. Bermasalah dengan lingkungan sosialnya. Pribadi yang memiliki konsep diri negatif merasa kurang mampu berinteraksi dengan orang lain.
D. Mengembangkan Perkembangan Konsep Diri
Konsep diri terbentuk melalui proses belajar sejak masapertumbuhan seseorang manusia dari kecil hingga dewasa. Lingkungandan pengalaman orang tua turut memberikan pengaruh yang signifikanterhadap konsep diri yang terbentuk. Sikap orang tua dan lingkungan akanmenjadi bahan informasi bagi anak untuk tumbuh menilai siapadirinya.Lingkungan yang kurang mendukung akan membentuk konsep diri yangnegatif. Jika lingkungan dan orang tua mendukung dan memberikan sifatbaik akan membentuk konsep diri siswa yang positif.
Menurut Charles Horton Cooleykonsep diri dapat dimunculkan dengan melakukanpembayangan diri sendiri sebagai orang lain, yang disebutnya sebagailooking-glass self (diri-cermin) seakan-akan kita menaruh cermindihadapan kita sendiri. Prosesnya dimulai dengan membayangkanbagaimana kita tampak pada orang lain, kita melihat sekilas diri kitaseperti dalam cermin. Misalnya, kita merasa wajah kita menarik atau tidakmenarik. Proses kedua, kita membayangkan bagaimana orang lain menilaipenampilan kita. Apakah orang lain menjadi kita menarik, cerdas atautidak menarik. Proses ketiga, kita kemudian mengalami perasaan banggaatau kecewa atas percampuran penilaian diri kita sendiri dan penilaianorang lain. Jika penilaian kita terhadap diri sendiri positif, dan orang lainpun menilai kita positif, maka kita kemudian mengembangkan konsep diriyang positif. Begitu sebaliknya, penilaian orang lain terhadap diri kitanegatif, dan kita pun menilai diri kita negatif, maka kemudian kitamengembangkan konsep diri yang negatif.
Menurut Verderber, upaya mengembangkan perkembangan konsip diri indovidu dapat dilakukan dengan cara:
a. Self-appraisal
Istilah ini menunjukkan suatu pandangan yang menjadikan diri sendirisebagai objek dalam komunikasi atau dengan kata lain adanya kesankita terhadap diri kita sendiri.
b. Reaction and Response of Others
Konsep diri itu tidak saja berkembang melalui pandangan kita terhadap diri sendiri, namun berkembang dalam rangka interaksi kita denganmasyarakat. Dengan demikian apa yang ada pada diri kita dievaluasioleh orang lain melalui interaksi kita dengan orang tersebut, dan padagilirannya evaluasi masing-masing individu mempengaruhiperkembangan konsep diri kita.
c. Roles You Play-Role Taking
Peran memiliki pengaruh terhadap konsep diri, adanya aspek peranyang kita mainkan sedikit banyak akan mempengaruhi konsep diriindividu. Peran yang individu mainkan itu adalah hasil dari sistem nilaiindividu. Individu dapat memotret diri sebagai individu yang bermainsesuai persepsi yang didasarkan pada pengalaman diri sendiri, yang didalamnya terdapat unsur selektivitas dari keinginan individu untukmemainkan peran.
d. Reference Groups
Konsep diri individu juga terbentuk dari adanya kelompok yangbercirikan individu itu terkumpul dalam suatu kelompok ataukomunitas yang diiinginkan. Setiap kelompok tersebut mempunyaiikatan enosional yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadappembentukan konsep diri individu. Dalam kelompok tersebut individuakan mengarahkan perilakunya dan menyesuaikan dirinya sesuaidengan ciri-ciri dan karakteristik kelompoknya itu. Artinya jika kelompok ini kita anggap penting dalam arti mereka dapat menilai dan bereaksi pada kita, hal ini akan menjadi kekuatan untuk menentukan konsep diri. Jadi cara kita menilai diri kita merupakan bagian darifungsi kita dievaluasi oleh kelompok rujukan.
e. Berpikir positif
Segala sesuatu tergantung pada cara kita memandang segala sesuatubaik terhadap persoalan maupun terhadap seseorang, artinyakendalikan pikiran jika pikiran itu mulai menyesatkan jiwa dan raga.
f. Jangan memusuhi diri sendiri
Sikap menyalahkan diri sendiri yang berlebihan merupakan pertandabahwa ada permusuhan dengan kenyataan diri akan menimbulkan konsep diri yang negatif.

http://togaptartius.com/
E. Pengaruh Konsep Diri Terhadap Prestasi
1. Pengertian Prestasi
Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai oleh seseorang setelah ia melakukan perubahan belajar, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Webster’s New International Dictionarymengungkapkan bahwa prestasi adalah : “Achievement test a standardised test for measuring the skill or knowledge by person in one more lines of work a sudy”.[18]Prestasi adalah tes standaruntuk mengukur kecakapan atau pengetahuan bagi seseorang dalam satu atau lebih garis-garis pekerjaan atau belajar. Prestasi belajar yang dicapai seorang individu merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhinya baik dari dalam diri (faktor internal) maupun dari luar diri (faktor eksternal) individu.
Sumber penguat belajar dapat secara ekstrinsik (nilai, pengakuan, penghargaan) dan dapat secara intrinsik (kegairahan untuk menyelidiki, mengartikan situasi). Prestasi belajar ialah hasil usaha bekerja atau belajar yang menunjukkan ukuran kecakapan yang dicapai. Siswa harus memiliki prestasi belajar yang baik demi terciptanya manusia yang berkualitas dan berprestasi tinggi. Prestasi belajar merupakan tolak ukur maksimal yang telah dicapai siswa setelah melakukan proses belajar selama waktu yang ditentukan. Prestasi belajar siswa banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik berasal dari dalam dirinya (internal) maupun dari luar dirinya (eksternal).
2. Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar
Faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar yang dikhusukan ke konsep diri, adalah adanya konsep diri yang tinggi.Konsep diri yang tinggi akan memudahkan siswa belajar secara teratur dan terarah. Sedangkan konsep diri rendah akan menjadikan seseorang memiliki perasaan tidak mampu memahami diri sendiri, rendah diri, sehinggasiswa tersebut menjadi minder bergaul danmengurangi interaksi di sekolah. Selain itu konsep diri yang tinggi menjadikan seeorang menjadi percaya diri atas apa yang dimilikinya sehingga menjadikan seseorang agar selalu berpikir positif terhadap dirinya sendiri.
3. Hubungan Konsep Diri terhadap Prestasi Belajar
Konsep diri menjadikan seseorang melakukan suatu perbuatan tertentu sehingga konsep diri sangat dibutuhkan dalam membentuk kepribadian seseorang.Prestasi belajar dapat ditentukan oleh berbagai aspek salah satunya adalah konsep diri. Ketika seorang individu mempunyai konsep diri yang baik sehingga dapat melahirkan suatu pola berpikir yang positif, maka hal itu akan memudahkan seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang terarah. Hubungan konsep diri dengan prestasi diantaranya:
a. Meningkatkan Motivasi
Motivasi yang tumbuh dari dalam diri seseorang (internal) maupun dari luar diri seseorang (eksternal) dapat mempengaruhi konsep diri yang akan dibentuk dan dibangun sehingga hal itu menjadi salah satu pemicu pembentukan kepribadian. Jika seseorang mempunyai konsep diri yang positif, maka hal itu dapat meningkatakan motivasi seseorang dan mendorongnya untuk melakukan suatu dalam meningkatkan prestasi belajar.
b. Meningkatkan rasa percaya diri
Ketika seseorang sudah memiliki konsep diri yang positif, maka akan melahirkan rasa percaya diri di dalam diriya. Sehingga memudahkan seseorang untuk berinteraksi dan melakukan berbagai macam kegiatan yang dapat menunjang prestasi belajar seseorang.
c. Menjadikan seseorang memahami dirinya, baik kelebihan dan kekurangannya
Konsep diri yang positif menjadikan seseorang lebih memahami siapa dirinya, kemampuannya dan kekurangannya. Jika seseorang telah mengetahui kelebihan dan kekuranagnnya, maka ia akan mengetahui hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu seperti hal nya prestasi belajar.
d. Menjadikan seseorang untuk berpikir positif
Pikiran positif yang ada pada diri seseorang berasal dari pengkonsepan seseorang mengenai dirinya sendiri.Hal itu terbentuk dari faktor internal maupun eksternal. Ketika seseorang dapat berpikir positif mengenai berbagai hal termasuk mengenal diri sendiri maka itu akan memudahkannya untuk mencapai prestasi belajar yang baik.
e. Memudahkan seseorang dalam belajar
Konsep diri yang positif akan melahirkan berbagai hal yang positif seperti berpikir positif, motivasi, pemahaman terhadap diri sendiri, meningkatkan rasa percaya diri, dan lain sebagainya. Dengan adanya pengkonsepan diri yang positif, maka akan memudahkan seseorang dalam mencapai tujuannya. Memudahkan seseorang dalam proes belajar, sehingga dapat menunjang prestasi belajar yang baik.
[1]Avin Fadilla Helmi, Gaya Kelekatan dan Konsep Diri, Jurnal Psikologi 1999 UGM hal. 9.
[2]Jalaludin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, Edisi Revisi, Penerbit Rosda Karya, hal. 99-100.
[3]Rina Oktaviana, Hubungan Antara Penerimaan Diri terhadap Cara-Cara Perkembangan Sekunder dengan Konsep Diri pada Remaja Puteri SLTPN 10 Yogyakarta hal.3-4.
[4]Ibid hal.4.
[5]Lita H Wulandari & Pasti Rola, Konsep Diri dan Motivasi Berprestasi Remaja Penghuni Panti Asuhan, Jurnal Pemberdayaan Komunitas, Mei 2004, Volume 3, Nomor 2 hal. 81-82.
[6]Nina Mutmainah, Psikologi Komunikasi, Universitas Terbuka, 1999 hal. 101.
[7]Salbiah, Konsep Diri, Program Studi Ilmu Keperawatan, 2006, USU Repository.
[8]Ibid hal. 6.
[9]Ibid hal. 6.
[10]Potter & Perry, 2005, Buku Ajar Fundamental Keperawatan, Jakarta.
[11]Stuart & Sundeen, 2005, Buku Ajar Keperawatan Jiwa, Jakarta.
[12]Anna Keliat, 2005, Proses Keperawatan Kesehatan, Jiwa Edisi 2, Jakarta.
[13]Anna Keliat, 2005, Proses Keperawatan Kesehatan Jiwa Edisi 2, Jakarta.
[14]Stuart & Sundeen, 1998, Buku Saku Keperawatan Jiwa, Jakarta.
[15]Ibid.
[16]Anna Keliat, 1995, Proses Keperawatan Kesehatan Jiwa Edisi I, Jakarta.
[17]Lita H Wulandari & Pasti Rola, 2004, Konsep Diri dan Motivasi Berprestasi Remaja Penghuni Panti Asuhan, Jurnal Pemberdayaan Komunitas Volume 3, Nomor 2, hal. 83.
[18]Haji Djaali.(2012). Psikologi Pendidikan.Jakarta: Bumi Aksara.